Pengantar Kemampuan Bahasa Kedua
Kemampuan Bahasa Kedua (B2) mengacu pada kapasitas seseorang untuk mempelajari dan menggunakan bahasa selain bahasa pertama (B1), biasanya dalam konteks formal atau sosial. Istilah ini berbeda dari foreign language acquisition yang lebih sering terjadi dalam konteks pendidikan formal tanpa kebutuhan komunikasi sehari-hari. Contoh: Seorang anak Indonesia yang belajar Bahasa Inggris di sekolah sebagai mata pelajaran
PSIKOLINGUISTIK
Aco Nasir
5/6/202517 min read
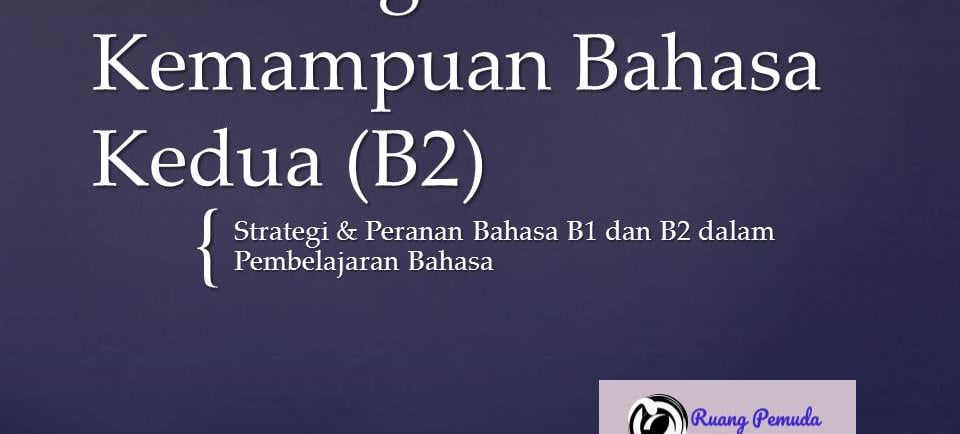
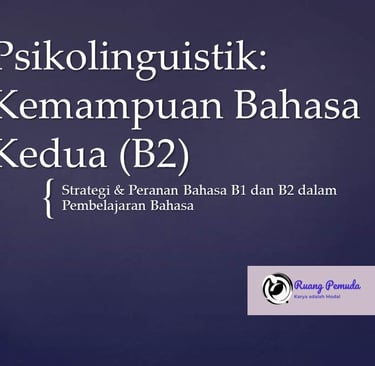
Topik 5: Kemampuan Bahasa Kedua (B2)
A. Pengantar Kemampuan Bahasa Kedua
Kemampuan Bahasa Kedua (B2) mengacu pada kapasitas seseorang untuk mempelajari dan menggunakan bahasa selain bahasa pertama (B1), biasanya dalam konteks formal atau sosial. Istilah ini berbeda dari foreign language acquisition yang lebih sering terjadi dalam konteks pendidikan formal tanpa kebutuhan komunikasi sehari-hari.
Contoh:
Seorang anak Indonesia yang belajar Bahasa Inggris di sekolah sebagai mata pelajaran.
B. Proses Pemerolehan Bahasa Kedua
Pemerolehan Bahasa Kedua dapat terjadi secara:
Alami (Natural Acquisition): Terjadi tanpa instruksi formal, dalam lingkungan yang mendukung komunikasi langsung.
Terpimpin (Instructed Learning): Melalui proses pembelajaran formal di kelas.
Faktor-faktor yang memengaruhi:
Usia
Motivasi
Paparan bahasa
Strategi pembelajaran
Transfer dari B1 ke B2
Proses Pemerolehan Bahasa Kedua (Second Language Acquisition)
Pemerolehan bahasa kedua atau second language acquisition (SLA) merujuk pada proses di mana seseorang mempelajari bahasa lain selain bahasa pertama atau bahasa ibu (B1). SLA merupakan bidang multidisipliner yang mencakup linguistik, psikologi, pendidikan, dan neurosains, dan penting dalam memahami bagaimana individu memperoleh kemampuan berbahasa kedua (B2) dalam berbagai konteks sosial dan pendidikan.
1. Pemerolehan Bahasa Kedua secara Alami (Natural Acquisition)
Pemerolehan alami terjadi ketika seseorang memperoleh bahasa kedua dalam lingkungan yang mendukung komunikasi langsung dan otentik, tanpa instruksi formal. Ini sering kali dialami oleh anak-anak imigran yang tinggal di negara yang menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa ibu mereka. Mereka belajar bahasa tersebut melalui interaksi sehari-hari di lingkungan sosial seperti taman bermain, rumah, atau media, bukan dari pelajaran di kelas.
Stephen Krashen (1982), seorang tokoh penting dalam teori SLA, membedakan antara language acquisition dan language learning. Acquisition adalah proses bawah sadar yang mirip dengan pemerolehan bahasa pertama, dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial serta keterlibatan emosional. Dalam konteks ini, pemerolehan terjadi melalui pemaparan bahasa secara alami, di mana pemelajar fokus pada makna, bukan bentuk. Salah satu teori kunci Krashen adalah Input Hypothesis, yang menyatakan bahwa bahasa diperoleh ketika seseorang terpapar pada input linguistik yang sedikit lebih tinggi dari tingkat kemampuannya saat ini (i + 1).
Contohnya, seorang anak yang baru pindah ke Jerman dari Turki mungkin tidak memahami banyak hal dalam beberapa bulan pertama. Namun, dengan terus mendengarkan dan mencoba berinteraksi dalam bahasa Jerman, mereka mulai memahami makna ujaran orang lain dan akhirnya mampu berbicara dalam bahasa tersebut.
2. Pemerolehan Bahasa Kedua secara Terpimpin (Instructed Learning)
Pemerolehan terpimpin terjadi dalam konteks formal seperti ruang kelas, di mana bahasa kedua diajarkan secara sistematis. Metode ini biasanya melibatkan pembelajaran tata bahasa, kosakata, keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis secara eksplisit.
Menurut Ellis (2008), pembelajaran terpimpin memainkan peran penting dalam SLA, terutama bagi orang dewasa yang belajar bahasa kedua dalam konteks di mana penggunaan bahasa target dalam kehidupan sehari-hari terbatas. Dalam konteks ini, instruksi eksplisit dapat membantu meningkatkan kesadaran linguistik dan mempercepat pemahaman terhadap struktur bahasa.
Namun, Ellis juga mencatat bahwa pembelajaran formal saja tidak cukup. Dibutuhkan praktik komunikasi otentik untuk mengembangkan kompetensi komunikatif. Oleh karena itu, pendekatan pengajaran komunikatif seperti Task-Based Language Teaching (TBLT) menjadi populer karena memadukan pembelajaran terpimpin dengan penggunaan bahasa dalam konteks tugas nyata.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerolehan Bahasa Kedua
Pemerolehan bahasa kedua tidak hanya dipengaruhi oleh metode pembelajaran, tetapi juga oleh berbagai faktor kognitif, sosial, dan afektif. Berikut adalah faktor-faktor utama yang berpengaruh:
a. Usia
Usia merupakan salah satu faktor paling kontroversial dalam SLA. Banyak penelitian mendukung teori Critical Period Hypothesis (CPH) yang menyatakan bahwa ada periode waktu optimal untuk memperoleh bahasa secara alami—biasanya sebelum pubertas (Lenneberg, 1967).
Anak-anak cenderung lebih mudah memperoleh pelafalan dan struktur tata bahasa seperti penutur asli jika mulai belajar sejak dini. Namun, orang dewasa sering kali lebih cepat dalam mempelajari aturan tata bahasa karena kemampuan metakognitif yang lebih baik. Menurut Birdsong (2006), meskipun kemampuan belajar bahasa menurun dengan usia, orang dewasa tetap mampu menjadi pembicara fasih dalam B2, tergantung pada motivasi dan lingkungan belajar mereka.
b. Motivasi
Motivasi adalah pendorong internal yang sangat penting dalam SLA. Gardner dan Lambert (1972) membedakan antara dua jenis motivasi:
· Motivasi integratif: Keinginan untuk menjadi bagian dari komunitas budaya bahasa target.
· Motivasi instrumental: Mempelajari bahasa untuk tujuan praktis seperti karier atau pendidikan.
Pemelajar dengan motivasi tinggi, baik integratif maupun instrumental, cenderung menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dan bertahan lama dalam proses pembelajaran bahasa. Dörnyei (2001) menambahkan bahwa motivasi tidak statis dan dapat dipengaruhi oleh pengalaman belajar serta persepsi terhadap kemampuan diri.
c. Paparan Bahasa (Exposure)
Frekuensi dan kualitas paparan terhadap bahasa target sangat penting. Paparan dapat berupa mendengarkan musik, menonton film, membaca buku, atau berkomunikasi dengan penutur asli. Semakin tinggi tingkat eksposur, semakin besar peluang seseorang untuk memahami dan menggunakan bahasa dengan lebih baik.
Paparan yang bermakna, sebagaimana diteorikan dalam Comprehensible Input oleh Krashen (1982), harus berada pada tingkat yang sedikit lebih kompleks daripada tingkat kemampuan pemelajar saat ini. Paparan pasif saja (seperti mendengarkan) tidak cukup tanpa keterlibatan aktif dalam menggunakan bahasa tersebut.
d. Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran mengacu pada teknik atau pendekatan yang digunakan pemelajar untuk memperoleh, menyimpan, dan menggunakan bahasa. Oxford (1990) mengklasifikasikan strategi pembelajaran ke dalam beberapa kategori, termasuk:
· Kognitif: menghafal, menganalisis, menerjemahkan
· Metakognitif: merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pembelajaran
· Sosial: bekerja sama dengan orang lain
· Afektif: mengelola emosi dan kecemasan
Penggunaan strategi yang bervariasi dan sesuai dapat mempercepat proses pembelajaran dan membantu pemelajar menjadi lebih mandiri.
e. Transfer dari Bahasa Pertama (B1)
Transfer bahasa adalah fenomena di mana struktur atau kebiasaan dari B1 dibawa ke dalam B2. Transfer ini bisa bersifat positif maupun negatif:
· Transfer positif terjadi ketika struktur B1 mirip dengan B2, sehingga mempermudah proses pembelajaran.
· Transfer negatif (interferensi) terjadi ketika terdapat perbedaan signifikan antara B1 dan B2, yang dapat menyebabkan kesalahan.
Contohnya, penutur bahasa Spanyol mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan bentuk waktu (tenses) bahasa Inggris karena perbedaan penggunaan dalam dua bahasa tersebut. Namun, penutur bahasa Jerman mungkin lebih mudah mempelajari struktur pasif dalam bahasa Inggris karena kesamaan dalam tata bahasanya.
Ellis (2008) mencatat bahwa transfer bukan hanya soal struktur gramatikal, tetapi juga menyangkut aspek fonologis, leksikal, dan pragmatis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan antara B1 dan B2 sangat penting dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif.
Proses pemerolehan bahasa kedua adalah topik yang kompleks dan melibatkan banyak aspek, baik dari sisi psikologis, kognitif, maupun sosial. Pemerolehan dapat terjadi secara alami maupun terpimpin, masing-masing dengan kelebihan dan tantangannya. Berbagai faktor seperti usia, motivasi, paparan bahasa, strategi pembelajaran, dan transfer dari bahasa pertama berperan penting dalam menentukan sejauh mana seorang pemelajar dapat menguasai bahasa kedua dengan efektif.
Memahami dinamika ini sangat penting bagi guru, pengembang kurikulum, dan pembelajar itu sendiri untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan dalam pemerolehan bahasa kedua. Intervensi pendidikan yang efektif sebaiknya mempertimbangkan konteks sosial, karakteristik individu pemelajar, serta memberikan paparan dan praktik berbahasa yang autentik dan bermakna.
Strategi Kemampuan Bahasa Kedua (B2)
A. Strategi Kognitif
Strategi ini berkaitan dengan proses mental dalam memahami dan menghasilkan bahasa, misalnya:
Menghafal kosakata
Menerjemahkan secara mental
Mengelompokkan informasi linguistik
Menyusun kalimat secara logis
Strategi Kemampuan Bahasa Kedua (B2): Fokus pada Strategi Kognitif
Dalam dunia pembelajaran bahasa kedua (B2), strategi belajar memegang peranan penting dalam keberhasilan pemelajar. Strategi belajar bahasa mencakup perilaku, teknik, atau pendekatan yang digunakan oleh individu untuk memfasilitasi pemerolehan, penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan bahasa. Salah satu jenis strategi yang paling menonjol adalah strategi kognitif, yaitu strategi yang secara langsung melibatkan pemrosesan informasi bahasa.
Strategi kognitif merupakan bagian dari taksonomi strategi pembelajaran bahasa yang banyak dijelaskan oleh Rebecca Oxford (1990) dalam bukunya yang terkenal Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Strategi ini mencakup berbagai aktivitas mental yang digunakan pemelajar untuk memanipulasi dan mentransformasikan bahasa target agar lebih mudah dipelajari dan dipahami.
A. Definisi Strategi Kognitif dalam Pembelajaran Bahasa Kedua
Strategi kognitif mengacu pada proses mental yang digunakan pemelajar untuk mengatasi tantangan linguistik. Menurut Oxford (1990), strategi kognitif melibatkan manipulasi langsung terhadap materi bahasa melalui latihan, analisis, pengelompokan, dan pemahaman makna. Strategi ini berbeda dari strategi metakognitif, yang lebih berfokus pada perencanaan dan pengawasan proses belajar.
Cohen (2011) menjelaskan bahwa strategi kognitif sangat penting karena strategi ini memungkinkan pemelajar untuk terlibat aktif dalam pemrosesan linguistik dan membangun pengetahuan secara sistematis. Tanpa strategi ini, pemelajar mungkin kesulitan menginternalisasi bahasa yang mereka pelajari, terutama ketika menghadapi struktur yang berbeda dari bahasa pertama mereka.
B. Bentuk-Bentuk Strategi Kognitif
Beberapa strategi kognitif yang umum digunakan dalam pemerolehan bahasa kedua antara lain:
1. Menghafal Kosakata
Menghafal atau memorization adalah strategi yang paling dasar namun vital dalam belajar bahasa kedua. Kosakata adalah fondasi dari kemampuan berbahasa. Tanpa kosakata yang cukup, komunikasi tidak dapat terjadi.
Pemelajar sering menggunakan berbagai teknik menghafal seperti:
· Pengulangan (rote repetition)
· Flashcards
· Asosiasi visual dan verbal
· Teknik mnemonik
Nation (2001) menyatakan bahwa pemelajar perlu mengenal sekitar 2.000–3.000 kata umum dalam bahasa target untuk bisa membaca teks sederhana secara efektif. Oleh karena itu, mengembangkan kosakata melalui strategi kognitif sangat penting dalam tahap awal pembelajaran bahasa.
2. Menerjemahkan secara Mental
Banyak pemelajar B2, terutama pada tahap awal, menggunakan strategi menerjemahkan dari B2 ke B1 atau sebaliknya sebagai cara memahami makna kata atau kalimat. Meskipun strategi ini sering dianggap tidak ideal oleh beberapa pengajar karena bisa memperlambat komunikasi, penelitian menunjukkan bahwa penerjemahan mental bisa menjadi jembatan penting dalam proses internalisasi makna.
Menurut Cook (2010), terjemahan mental adalah bagian alami dari bilingualisme dan tidak selalu berdampak negatif. Dalam konteks belajar bahasa, penerjemahan membantu pemelajar menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama.
Namun, seiring waktu dan dengan latihan yang cukup, pemelajar disarankan untuk mengurangi ketergantungan pada terjemahan dan mulai berpikir langsung dalam bahasa target untuk meningkatkan kelancaran (fluency).
3. Mengelompokkan Informasi Linguistik
Strategi pengelompokan atau grouping melibatkan pengkategorian kata atau struktur berdasarkan kesamaan makna, bentuk, atau fungsi. Misalnya, pemelajar bisa mengelompokkan kosakata berdasarkan tema (misalnya: kata kerja memasak, bagian tubuh, dll) atau berdasarkan kelas kata (noun, verb, adjective).
Oxford (1990) mengemukakan bahwa pengelompokan membantu memperkuat penyimpanan dalam memori jangka panjang dan memudahkan pemanggilan kembali informasi. Dengan mengorganisasi informasi, pemelajar bisa lebih mudah membentuk koneksi semantik dan sintaktik antara elemen bahasa.
Contohnya:
· Mengelompokkan kata kerja tidak beraturan (go, went, gone)
· Mengelompokkan frasa idiomatik berdasarkan arti konotatifnya
· Mengkategorikan kosakata berdasarkan registrasi formal/informal
4. Menyusun Kalimat Secara Logis
Strategi ini melibatkan kemampuan pemelajar dalam membentuk kalimat dengan susunan kata yang benar sesuai dengan struktur bahasa target. Penyusunan logis ini melibatkan pengetahuan tentang urutan subjek-predikat-objek, penggunaan waktu, kesesuaian subjek dan kata kerja, serta struktur tata bahasa lainnya.
Ellis (2003) menyatakan bahwa kemampuan menyusun kalimat secara logis menandakan bahwa pemelajar tidak hanya memahami elemen linguistik secara terpisah, tetapi juga mampu menggabungkannya menjadi satu kesatuan bermakna. Strategi ini sangat penting dalam keterampilan berbicara dan menulis, di mana koherensi dan kohesi merupakan komponen utama dari komunikasi yang efektif.
Misalnya, pemelajar bisa menggunakan strategi:
· Melengkapi kerangka kalimat (template-based sentence building)
· Mengikuti pola struktur kalimat dalam latihan
· Menggunakan substitusi dan transformasi kalimat
C. Peran Strategi Kognitif dalam Pemerolehan Bahasa Kedua
Strategi kognitif berkontribusi besar terhadap keberhasilan pemelajar dalam berbagai keterampilan bahasa: membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Keunggulan utama dari strategi kognitif adalah bahwa strategi ini melatih pemelajar untuk berpikir dan bekerja langsung dengan materi bahasa. Hal ini meningkatkan keterlibatan aktif dan mempercepat pemrosesan informasi linguistik.
Penelitian oleh Chamot dan O’Malley (1994) menunjukkan bahwa pemelajar yang dilatih menggunakan strategi kognitif secara sadar menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman bacaan dan produksi tulisan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi tidak hanya muncul secara alami, tetapi juga bisa diajarkan dan dilatih secara eksplisit.
D. Implikasi dalam Pengajaran Bahasa Kedua
Bagi pendidik, memahami strategi kognitif sangat penting untuk merancang pengajaran yang responsif terhadap gaya belajar siswa. Guru dapat:
· Memberikan pelatihan strategi secara eksplisit
· Memberikan latihan-latihan yang mendorong penggunaan strategi kognitif
· Memberikan umpan balik terhadap strategi yang digunakan siswa
· Mendorong refleksi atas efektivitas strategi yang telah dicoba
Guru juga dapat menggunakan instrumen seperti Language Learning Strategy Inventory untuk mengidentifikasi strategi yang paling sering digunakan siswa, kemudian menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan hasil tersebut (Oxford, 1990).
Strategi kognitif adalah komponen penting dalam pembelajaran bahasa kedua yang melibatkan aktivitas mental seperti menghafal, menerjemahkan, mengelompokkan, dan menyusun kalimat. Penggunaan strategi ini membantu pemelajar dalam memproses dan menginternalisasi bahasa target secara lebih efisien. Setiap strategi memiliki kelebihan tersendiri dan dapat digunakan secara fleksibel tergantung pada tujuan belajar dan karakteristik pemelajar.
Pemahaman terhadap strategi kognitif tidak hanya penting bagi pemelajar, tetapi juga bagi guru bahasa yang ingin membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri, reflektif, dan efektif. Dengan menerapkan pendekatan yang berpusat pada strategi, pembelajaran bahasa kedua menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada hasil jangka panjang.
B. Strategi Metakognitif
Strategi ini digunakan untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar bahasa, contohnya:
Menentukan tujuan belajar
Mengatur waktu belajar
Menilai efektivitas metode belajar
Strategi Metakognitif dalam Pembelajaran Bahasa Kedua (B2)
Dalam konteks pemerolehan bahasa kedua (B2), strategi pembelajaran berperan penting dalam mendukung keberhasilan pemelajar untuk memahami, menggunakan, dan menginternalisasi bahasa target. Salah satu jenis strategi yang paling krusial adalah strategi metakognitif. Berbeda dari strategi kognitif yang berkaitan langsung dengan pemrosesan materi bahasa, strategi metakognitif berfokus pada bagaimana pemelajar mengatur, mengarahkan, dan mengevaluasi proses belajar mereka secara menyeluruh.
A. Definisi Strategi Metakognitif
Strategi metakognitif dapat diartikan sebagai tindakan sadar yang dilakukan pemelajar untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar mereka. Strategi ini membantu pemelajar dalam membuat keputusan yang efektif mengenai pendekatan terbaik dalam mempelajari bahasa, termasuk kapan, bagaimana, dan dengan cara apa mereka belajar.
Menurut O’Malley dan Chamot (1990), strategi metakognitif mencakup perencanaan belajar, pengawasan pemahaman atau kinerja diri, serta penilaian terhadap hasil belajar. Dengan kata lain, strategi ini menjadikan pemelajar lebih reflektif dan mandiri, sehingga mereka dapat mengontrol proses belajar bahasa secara proaktif.
Oxford (1990) menyatakan bahwa strategi metakognitif sering digunakan oleh pemelajar yang berhasil dan efektif. Hal ini karena mereka tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga belajar bagaimana belajar bahasa. Mereka mampu melihat gambaran besar, merencanakan tindakan, dan merevisi pendekatan bila diperlukan.
B. Komponen Strategi Metakognitif
Strategi metakognitif terdiri atas beberapa bentuk tindakan spesifik, di antaranya:
1. Menentukan Tujuan Belajar
Penetapan tujuan merupakan langkah awal yang penting dalam strategi metakognitif. Dengan tujuan yang jelas, pemelajar memiliki arah dalam proses belajarnya. Tujuan dapat bersifat jangka pendek (misalnya: menguasai 20 kosakata baru dalam seminggu) atau jangka panjang (misalnya: mampu berbicara lancar dalam bahasa Inggris dalam waktu enam bulan).
Zimmerman (2002) menyebut penetapan tujuan sebagai inti dari pengaturan diri dalam belajar. Tujuan belajar yang spesifik, terukur, dan realistis membantu pemelajar untuk tetap termotivasi dan fokus pada pencapaian yang ingin diraih.
Contoh praktik dalam pembelajaran bahasa:
· Membuat daftar harian/mingguan tentang apa yang ingin dipelajari.
· Menuliskan target seperti “hari ini saya akan menguasai penggunaan present perfect.”
2. Mengatur Waktu Belajar
Pengaturan waktu merupakan bagian penting dalam perencanaan belajar. Pemelajar bahasa yang menggunakan strategi metakognitif akan menentukan kapan dan berapa lama waktu belajar yang dibutuhkan, dan bagaimana waktu tersebut dapat digunakan secara efisien.
Menurut Vandergrift (2005), salah satu ciri pemelajar bahasa yang efektif adalah kemampuannya dalam mendistribusikan waktu belajar untuk berbagai keterampilan bahasa seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan.
Contoh pengaturan waktu:
· Menyisihkan waktu 30 menit setiap hari untuk berlatih mendengarkan audio bahasa target.
· Mengatur jadwal belajar secara mingguan dengan rotasi fokus keterampilan.
3. Memantau Proses Belajar
Pemantauan (monitoring) adalah kemampuan untuk mengawasi apakah proses belajar berjalan sesuai rencana. Pemelajar yang menerapkan strategi ini biasanya bertanya pada diri sendiri:
· Apakah saya memahami materi ini?
· Apakah strategi belajar saya berhasil?
· Apa yang perlu saya ubah?
Flavell (1979), pelopor konsep metakognisi, menjelaskan bahwa monitoring merupakan bagian inti dari kesadaran metakognitif. Dalam konteks pembelajaran bahasa, monitoring mencakup refleksi selama membaca, mendengarkan, atau berbicara dalam bahasa target.
Contoh monitoring dalam pembelajaran:
· Mengecek pemahaman setelah membaca teks.
· Merekam percakapan lalu mendengarkannya kembali untuk menilai kefasihan.
4. Menilai Efektivitas Metode Belajar
Evaluasi merupakan tahap akhir dalam strategi metakognitif. Pada tahap ini, pemelajar menilai apakah metode yang digunakan memberikan hasil yang diinginkan. Bila tidak, mereka akan mencoba strategi lain yang lebih efektif.
Chamot et al. (1999) menyatakan bahwa evaluasi memungkinkan pemelajar untuk memperbaiki pendekatan belajar mereka dan menghindari pengulangan kesalahan yang sama.
Contoh evaluasi:
· Setelah mengikuti kursus daring selama satu bulan, pemelajar menilai seberapa besar peningkatan yang dirasakan.
· Membandingkan dua metode belajar kosakata (flashcards vs. aplikasi) dan memilih yang lebih sesuai dengan gaya belajar pribadi.
C. Manfaat Strategi Metakognitif dalam Pembelajaran Bahasa Kedua
Penggunaan strategi metakognitif memiliki banyak manfaat, antara lain:
1. Meningkatkan Kemandirian Belajar
Pemelajar yang mampu mengatur dan mengawasi proses belajarnya sendiri menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung sepenuhnya pada guru atau lingkungan. Mereka bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sendiri, serta memilih strategi yang paling sesuai (Wenden, 1991).
2. Meningkatkan Efisiensi Waktu dan Energi
Dengan perencanaan dan pemantauan yang baik, pemelajar dapat menggunakan waktunya secara lebih produktif. Mereka belajar dengan cara yang paling efektif, menghindari pengulangan yang tidak perlu (Anderson, 2002).
3. Mendorong Refleksi dan Perbaikan Diri
Evaluasi memungkinkan pemelajar untuk merefleksikan proses belajar, mengenali kesalahan, dan memperbaiki pendekatan belajar. Refleksi ini penting untuk pertumbuhan sebagai pembelajar sepanjang hayat (Schraw & Moshman, 1995).
D. Penerapan Strategi Metakognitif dalam Pengajaran Bahasa
Agar strategi metakognitif dapat dimanfaatkan secara optimal, guru harus membantu siswa menyadari pentingnya strategi ini dan membimbing mereka dalam menerapkannya. Beberapa cara yang dapat dilakukan guru antara lain:
· Modeling: Guru secara eksplisit menunjukkan bagaimana membuat tujuan belajar dan memantau pemahaman.
· Think-Aloud: Guru menyuarakan proses berpikirnya saat membaca atau menyimak, agar siswa memahami cara berpikir metakognitif.
· Refleksi Tertulis: Memberi tugas bagi siswa untuk menulis jurnal belajar atau menilai kemajuan mereka sendiri.
· Diskusi Strategi: Mendorong siswa untuk saling berbagi strategi belajar yang mereka gunakan dan menilai keefektifannya.
Penelitian oleh Chamot et al. (1999) dalam Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) menunjukkan bahwa pelatihan strategi metakognitif yang terstruktur secara signifikan meningkatkan prestasi siswa dalam penguasaan bahasa kedua.
Kesimpulan
Strategi metakognitif memainkan peran sentral dalam pembelajaran bahasa kedua karena strategi ini memungkinkan pemelajar untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi pengalaman belajar mereka secara sistematis. Dengan menggunakan strategi ini, pemelajar menjadi lebih sadar diri, lebih reflektif, dan lebih mampu menyesuaikan pendekatan belajar mereka agar lebih efektif.
Pemahaman dan penerapan strategi metakognitif bukan hanya tanggung jawab pemelajar, tetapi juga harus difasilitasi oleh guru. Guru berperan penting dalam membimbing siswa untuk menjadi pembelajar bahasa yang otonom dan sadar strategi. Dengan demikian, strategi metakognitif merupakan jembatan penting menuju pembelajaran bahasa yang lebih bermakna, berkelanjutan, dan berhasil.
C. Strategi Sosial dan Afektif
Strategi ini melibatkan interaksi sosial dan kontrol emosi:
Bertanya kepada penutur asli
Diskusi kelompok
Mengelola kecemasan saat berbicara
Meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan B2
C. Strategi Sosial dan Afektif dalam Pemerolehan Bahasa Kedua
Dalam pembelajaran bahasa kedua (B2), strategi pembelajaran berperan penting dalam menunjang keberhasilan pemelajar. Salah satu klasifikasi strategi belajar yang sering digunakan dalam teori pemerolehan bahasa adalah strategi sosial dan afektif. Kedua strategi ini menekankan pentingnya faktor sosial (interaksi dengan orang lain) dan afektif (emosi, sikap, dan motivasi) dalam proses belajar bahasa.
Menurut Oxford (1990), strategi sosial dan afektif merupakan bagian dari strategi tidak langsung (indirect strategies), yakni strategi yang mendukung pembelajaran secara tidak langsung melalui pengelolaan kondisi eksternal dan internal. Strategi sosial dan afektif memfasilitasi lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan, memperkuat motivasi, serta mengurangi hambatan emosional yang sering kali muncul dalam proses belajar bahasa kedua.
A. Strategi Sosial dalam Pembelajaran Bahasa Kedua
Strategi sosial adalah strategi yang melibatkan pemelajar untuk berinteraksi dengan orang lain guna memperoleh informasi atau meningkatkan keterampilan berbahasa. Interaksi dengan penutur asli atau sesama pemelajar bahasa merupakan salah satu cara yang sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan B2, karena menyediakan konteks otentik untuk penggunaan bahasa.
1. Bertanya kepada Penutur Asli
Bertanya kepada penutur asli atau penutur mahir bahasa target adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bahasa dan budayanya. Interaksi langsung ini memungkinkan pemelajar untuk mempraktikkan bahasa secara nyata, memperbaiki pengucapan, serta memahami ekspresi idiomatik dan gaya bahasa sehari-hari.
Menurut Long (1996), interaksi dengan penutur asli menciptakan peluang untuk negotiation of meaning, yaitu proses di mana makna dinegosiasikan antara pembicara dan pendengar, sehingga terjadi perbaikan bahasa secara alami.
Contoh praktik:
· Bertanya kepada guru, tutor, atau teman sebaya mengenai makna kata atau struktur tertentu.
· Berpartisipasi dalam percakapan dengan penutur asli melalui media sosial, forum daring, atau program pertukaran bahasa.
2. Diskusi Kelompok
Diskusi kelompok membantu pemelajar membangun kepercayaan diri dan memperkuat keterampilan komunikasi. Diskusi memungkinkan pertukaran ide, klarifikasi pemahaman, dan penggunaan bahasa secara kontekstual. Selain itu, kegiatan ini mendukung pembelajaran kolaboratif, di mana siswa saling membantu mengatasi kesulitan.
Vygotsky (1978) dalam teorinya tentang zone of proximal development (ZPD) menekankan bahwa pembelajaran terjadi secara optimal ketika siswa bekerja bersama dan mendapatkan bantuan dari rekan yang lebih mahir. Diskusi kelompok merupakan wujud dari lingkungan belajar seperti ini.
Contoh kegiatan:
· Debat kelompok kecil menggunakan B2.
· Diskusi pemahaman bacaan atau video dalam bahasa target.
· Belajar kelompok dengan sistem tutor sebaya.
B. Strategi Afektif dalam Pembelajaran Bahasa Kedua
Strategi afektif berkaitan dengan bagaimana pemelajar mengelola emosi, sikap, dan motivasi mereka selama proses belajar bahasa. Emosi negatif seperti kecemasan, rendah diri, atau rasa takut membuat kesalahan dapat menghambat keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, strategi afektif penting untuk membantu pemelajar menciptakan kondisi psikologis yang mendukung proses belajar.
1. Mengelola Kecemasan saat Berbicara
Kecemasan (anxiety) merupakan salah satu hambatan paling umum dalam belajar bahasa kedua, terutama dalam konteks berbicara. Horwitz, Horwitz, dan Cope (1986) menyebutnya sebagai foreign language anxiety, yaitu perasaan gugup, takut, atau tidak nyaman saat harus menggunakan bahasa target di depan umum.
Strategi untuk mengelola kecemasan meliputi:
· Latihan pernapasan atau teknik relaksasi sebelum berbicara.
· Persiapan sebelumnya dengan cara menulis skrip atau berlatih dialog.
· Fokus pada pesan, bukan pada kesempurnaan struktur atau pengucapan.
Dengan mengelola kecemasan secara efektif, pemelajar akan merasa lebih percaya diri dan mampu tampil lebih baik dalam situasi komunikatif.
2. Meningkatkan Kepercayaan Diri dalam Menggunakan B2
Kepercayaan diri (self-confidence) merupakan aspek penting dalam keberhasilan belajar bahasa. Pemelajar yang percaya diri akan lebih berani mengambil risiko linguistik, seperti mencoba kosakata baru atau berbicara dalam situasi nyata. Menurut Bandura (1997), kepercayaan diri atau self-efficacy memengaruhi seberapa besar usaha yang dilakukan seseorang dan seberapa lama ia bertahan dalam menghadapi tantangan.
Beberapa strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri:
· Memberi penghargaan pada diri sendiri setelah mencapai target belajar.
· Mengingat kembali keberhasilan kecil dalam penggunaan bahasa.
· Menghindari perbandingan negatif dengan orang lain.
Pelibatan dalam aktivitas sosial yang menyenangkan dan tidak menghakimi juga membantu menumbuhkan kepercayaan diri.
C. Integrasi Strategi Sosial dan Afektif dalam Pengajaran Bahasa
Agar strategi sosial dan afektif efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa kedua, guru perlu menciptakan lingkungan kelas yang aman, inklusif, dan mendorong interaksi serta ekspresi diri. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara lain:
1. Penerapan Metode Komunikatif (Communicative Language Teaching - CLT):
Metode ini menekankan pada penggunaan bahasa secara nyata dalam konteks sosial. Guru dapat mendorong kegiatan role play, diskusi, permainan peran, dan tugas kolaboratif yang memerlukan kerja sama.
2. Pendekatan Humanistik:
Dalam pendekatan ini, emosi dan pengalaman pribadi siswa menjadi bagian dari proses belajar. Guru menunjukkan empati, menghindari koreksi yang mempermalukan, dan memberikan dukungan psikologis.
3. Penggunaan Teknologi Sosial:
Media sosial, forum, dan aplikasi pertukaran bahasa seperti Tandem atau HelloTalk dapat digunakan untuk memperluas peluang interaksi sosial siswa di luar kelas.
D. Pentingnya Kesadaran Strategi Sosial dan Afektif bagi Pemelajar
Kesadaran akan pentingnya strategi sosial dan afektif dapat membantu pemelajar memahami bahwa keberhasilan belajar tidak hanya bergantung pada pengetahuan linguistik, tetapi juga pada kemampuan untuk berinteraksi dan mengelola diri. Strategi ini menjadi pelengkap dari strategi kognitif dan metakognitif, menciptakan proses pembelajaran yang lebih seimbang secara emosional dan sosial.
Oxford (2011) menekankan bahwa pemelajar yang menggunakan strategi sosial dan afektif cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi, tingkat stres yang lebih rendah, dan hasil belajar yang lebih baik secara keseluruhan.
Strategi sosial dan afektif dalam pembelajaran bahasa kedua memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat kemampuan komunikasi serta meningkatkan kenyamanan dan keberanian pemelajar dalam menggunakan bahasa target. Melalui interaksi sosial seperti diskusi kelompok dan komunikasi dengan penutur asli, serta pengelolaan emosi seperti mengatasi kecemasan dan membangun kepercayaan diri, pemelajar dapat mengatasi hambatan non-linguistik yang sering kali lebih sulit daripada aspek kebahasaan itu sendiri.
Peran guru sangat penting dalam memfasilitasi penerapan strategi ini dengan menciptakan suasana belajar yang mendukung, memotivasi, dan inklusif. Dengan integrasi strategi sosial dan afektif, proses pemerolehan bahasa kedua menjadi lebih manusiawi, bermakna, dan berkelanjutan.
D. Strategi Kompensasi
Untuk mengatasi keterbatasan linguistik:
Menggunakan sinonim atau parafrase
Isyarat nonverbal (gesture)
Perkiraan makna dari konteks
Peranan Bahasa Pertama (B1) dan Bahasa Kedua (B2) dalam Pembelajaran Bahasa
A. Peranan Bahasa Pertama (B1):
Transfer Positif: Struktur B1 mirip dengan B2, sehingga memudahkan pembelajaran.
Transfer Negatif (Interferensi): Struktur B1 sangat berbeda dengan B2, dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan B2.
Sebagai landasan berpikir: B1 sering digunakan untuk memahami konsep dalam B2.
B. Peranan Bahasa Kedua (B2):
Sebagai alat komunikasi lintas budaya
Meningkatkan kemampuan kognitif dan akademik
Memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan global
C. Interaksi B1 dan B2 dalam Otak:
Otak bilingual mengaktifkan kedua bahasa dalam proses berpikir dan komunikasi.
Ada kemungkinan terjadinya code-switching dan code-mixing dalam interaksi bahasa sehari-hari.
Studi Kasus Singkat
Contoh: Seorang pelajar Indonesia yang menggunakan strategi mnemonik dan berbicara dengan penutur asli untuk meningkatkan Bahasa Inggrisnya. Ia sering mencampur Bahasa Indonesia dan Inggris (code-mixing) dalam percakapan informal.
Referensi
Ellis, R. (2008). The Study of Second Language Acquisition. Oxford University Press.
Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. Pearson Education.
Lightbown, P. M., & Spada, N. (2013). How Languages are Learned. Oxford University Press.
4. Birdsong, D. (2006). Age and second language acquisition and processing: A selective overview. Language Learning, 56(S1), 9–49. https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2006.00353.x
5. Dörnyei, Z. (2001). Motivational strategies in the language classroom. Cambridge University Press.
6. Ellis, R. (2008). The study of second language acquisition (2nd ed.). Oxford University Press.
7. Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). Attitudes and motivation in second-language learning. Newbury House Publishers.
8. Krashen, S. D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Pergamon Press.
9. Lenneberg, E. H. (1967). Biological foundations of language. Wiley.
10. Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Newbury House.
11. Chamot, A. U., & O’Malley, J. M. (1994). The CALLA handbook: Implementing the cognitive academic language learning approach. Addison-Wesley.
12. Cohen, A. D. (2011). Strategies in learning and using a second language (2nd ed.). Routledge.
13. Cook, V. (2010). Second language learning and language teaching (4th ed.). Routledge.
14. Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford University Press.
15. Nation, I. S. P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge University Press.
16. Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Newbury House.
Anderson, N. J. (2002). The role of metacognition in second language teaching and learning. ERIC Digest. https://www.ericdigests.org/2003-1/role.html
Chamot, A. U., Barnhardt, S., El-Dinary, P. B., & Robbins, J. (1999). The Learning Strategies Handbook. Addison Wesley Longman.
Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906–911. https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906
O’Malley, J. M., & Chamot, A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge University Press.
Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Newbury House.
Schraw, G., & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review, 7(4), 351–371.
Vandergrift, L. (2005). Relationships among motivation orientations, metacognitive awareness and proficiency in L2 listening. Applied Linguistics, 26(1), 70–89.
Wenden, A. (1991). Learner strategies for learner autonomy: Planning and implementing learner training for language learners. Prentice Hall.
Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into Practice, 41(2), 64–70.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman.
Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125–132. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1986.tb05256.x
Long, M. H. (1996). The role of the linguistic environment in second language acquisition. In W. C. Ritchie & T. K. Bhatia (Eds.), Handbook of second language acquisition (pp. 413–468). Academic Press.
Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Newbury House.
Oxford, R. L. (2011). Teaching and researching language learning strategies. Routledge.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.
Inspirasi
Kolaborasi
Pembelajaran
info@ruangpemuda.info
085145459727
© 2024. All rights reserved.
